Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di sejumlah daerah menunjukkan cenderung meningkatnya jumlah mereka yang tidak menggunakan hak memilih (golput). Dua pilkada terakhir di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, tingkat partisipasi masyarakat kurang dari 60 persen. Mengapa demikian dan sejauh mana fenomena golput mewarnai Pemilu 2009 mendatang?
Secara umum, ketidakhadiran sebagian masyarakat dalam memberikan suaranya dalam pemilu dan pilkada dapat dikategorikan atas dua kelompok.
Pertama, karena faktor teknis seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak memperoleh kartu pemilih, dan alasan-alasan lain yang bersumber pada kekacauan manajemen pemilihan.
Kedua, karena faktor politik seperti kekecewaan terhadap partai, kandidat yang diajukan partai, dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemilu dan pilkada mengubah kehidupan masyarakat. Hanya, data mereka yang tidak memilih sering tidak tersedia karena alasan teknis dan masyarakat golput karena faktor politik.
Golput karena faktor teknis sebenarnya tak perlu dikhawatirkan karena hal itu bisa berkurang jika kualitas manajemen pemilu dan pilkada dibenahi oleh komisi penyelenggara pemilihan. Penyebutan golput pun tidak tepat karena istilah yang berasal dari frasa ”golongan putih” itu ditujukan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena kecewa dengan sistem politik yang berlaku. Karena itu, yang tampaknya perlu menjadi perhatian adalah fenomena tidak menggunakan hak pilih akibat kekecewaan terhadap semua faktor yang terkait pemilu dan pilkada.
Ekspresi kekecewaan
Penilaian yang bersifat positif memandang, golput politik yang cenderung meningkat mencerminkan kian meluasnya kesadaran masyarakat akan sistem politik yang lebih demokratis, adil, dan berpihak kepada kepentingan umum. Sistem pemilu atau pilkada, mekanisme pencalonan kandidat, dan format penyelenggaraannya dipandang belum merepresentasikan partisipasi dan kepentingan publik. Pemilu dan pilkada lebih dilihat sebagai arena elite politik yang memiliki uang untuk mendapat kekuasaan, tetapi lalu mengkhianati mandat rakyat saat sudah terpilih. Meluasnya fenomena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang diindikasikan pengadilan terhadap para mantan wakil rakyat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan mantan menteri mencerminkan realitas itu.
Jadi, fenomena golput politik yang cenderung meningkat adalah ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap klaim-klaim keberhasilan reformasi dan demokratisasi yang dialami bangsa kita selama sekitar 10 tahun terakhir. Secara obyektif, kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada kian bebas dan demokratis. Dimulai pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat tahun 2004, diikuti pilkada langsung sejak Juni 2005. Indonesia bahkan dibanggakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS.
Namun, sebenarnya klaim keberhasilan dan kebanggaan itu bersifat semu karena yang meningkat secara signifikan sejak 1999 adalah demokrasi prosedural ketimbang demokrasi substansial. Demokrasi prosedural hanya menyediakan arena bagi elite untuk merebut kekuasaan, tetapi tanpa keberpihakan dan tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan bagi kepentingan umum. Tak mengherankan jika klaim keberhasilan demokratisasi berjalan seiring merosotnya kepercayaan publik terhadap partai, parlemen, dan lembaga demokrasi lainnya, seperti ditunjukkan oleh berbagai hasil survei selama ini.
Golput dan Pemilu 2009
Fenomena meningkatnya golput dalam sejumlah pilkada di provinsi dan kabupaten serta kota beberapa waktu terakhir tidak mustahil akan memuncak pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009. Kinerja pemerintah, parlemen, dan partai-partai yang masih buruk di tengah berbagai pidato dan jargon tentang keadilan, korupsi, dan pengentasan kemiskinan bisa menjadi faktor penting yang mendorong meluapnya ekspresi kekecewaan masyarakat dalam pemilu.
Apalagi jika pemilu mendatang tidak menawarkan format keterlibatan publik yang lebih meningkat, mekanisme pencalonan para kandidat yang lebih transparan dan demokratis serta tidak ada jaminan bagi lahirnya elite politik yang lebih bertanggung jawab. Undang-undang pemilu baru yang dihasilkan DPR bersama pemerintah juga tidak menjanjikan perubahan signifikan kendati berupaya melembagakan koherensi antara sistem kepartaian dan sistem presidensial melalui mekanisme parliamentary threshold 2,5 persen. Berbagai UU bidang politik pada akhirnya lebih merupakan ”aturan main” di antara para politisi ketimbang sebagai mekanisme untuk menerjemahkan aspirasi publik ke dalam sistem politik.
Ironisnya, partai-partai yang berkinerja buruk dan partai-partai baru yang juga belum jelas komitmennya itu ”harus” dipilih rakyat dalam pemilu legislatif mendatang. Di sisi lain, kandidat presiden yang tiap hari ditawarkan media adalah tokoh ”daur ulang” yang sebagian di antaranya terbukti gagal mengangkat harkat bangsa kita menjadi lebih baik. Kalaupun media mengiklankan kandidat presiden alternatif, yang diusung akhirnya hanya ”popularitas”, sementara rekam jejak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dibiarkan larut dalam sejarah.
Pertanyaannya, haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemungutan suara jika setelah pemilu ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya ”berpesta” di atas penderitaan rakyat?
Mungkin di sinilah letak urgensi kesadaran elite politik di partai, lembaga perwakilan, dan pemerintahan, bahwa fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tak lagi mampu bersuara. Ia bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak cerdas dan tak kunjung becus mengelola republik ini.
Syamsuddin Haris Profesor Riset Ilmu Politik LIPI
Syamsuddin Haris
Sumber : www.kompas.com

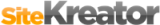
0 komentar:
Posting Komentar