(
Isu tentang krisis pangan dunia akhir-akhir ini telah mencemaskan banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga dunia seperti FAO, IMF, dan Bank Dunia. Di beberapa negara, kondisi ini bahkan telah munculkan krisis sosial. Di Haiti, misalnya, diberitakan
Kenaikan harga pangan memang terjadi sangat mencolok. Menurut sebuah sumber, Bloomberg Markets Magazine, harga Gandum naik sebesar 130%, Kedelai 87%, Beras 74%, dan Jagung 31%. Sementara itu menurut kepala Bank Dunia, Robert Zoellick, kenaikan pangan secara keseluruhan mencapai 83 persen dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan sebesar itu jelas tidak terjangkau oleh mayoritas masyarakat di negara berkembang, di mana 60% lebih pendapatan mereka habis untuk membeli kebutuhan makanan. Memang, bagi masyarakat di negara maju, kenaikan tersebut mungkin masih bisa dijangkau. Sebab, pada umumnya alokasi pendapatan mereka untuk kebutuhan makanan hanya sekitar 10-20% saja. Dengan kata lain, ada pilihan bagi mereka untuk mengurangi konsumsi non-makanan kemudian dialihkan untuk konsumsi makanan.
Menurut Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Dr. Jacques Diouf, ada
Jika krisis pangan diartikan sebagai kondisi di mana terdapat sejumlah populasi manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makannya, sehingga terjadi bencana kelaparan dan krisis sosial; maka ada dua kemungkinan hal itu bisa terjadi. Kemungkinan pertama, jumlah pangan tidak mencukupi kebutuhan seluruh populasi manusia, sehingga ada sebagian orang yang terpaksa tidak mendapatkan bagian makanan. Kemungkinan kedua, jumlah bahan pangan sebenarnya cukup, akan tetapi harganya terlalu tinggi. Akibatnya, ada sebagian orang yang tidak mampu membeli, sehingga tidak mendapatkan makanan.
Kemungkinan pertama bahwa krisis disebabkan oleh ketidakcukupan bahan pangan sangat diragukan. Sebab, jumlah pangan dunia sebenarnya cukup untuk mememenuhi kebutuhan seluruh populasi penduduk. Sebagai contoh, pada bulan Mei 1990, FAO (Food and Agricultural Organization) telah mengumumkan hasil studinya, bahwa produksi pangan dunia ternyata mengalami surplus 10% untuk dapat mencukupi seluruh populasi penduduk dunia. Namun, dalam kondisi seperti itu tetap saja ada sejumlah populasi manusia di dunia yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya hingga terjadi kelaparan, seperti yang terjadi di
Jika Direktur Jenderal FAO, Dr. Jacques Diouf, mengatakan ada
Sejak akhir Perang Dunia ke-2, jumlah penduduk dunia telah meningkat dua kali lipat, namun di sisi lain, jumlah produksi pangan dunia meningkat tiga kali lipat. Semua ini membuktikan bahwa krisis pangan bukan disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan, namun lebih disebabkan oleh kemungkinan kedua, yaitu tingginya harga pangan, yang mengakibatkan sebagaian orang tidak mampu untuk membelinya.
Sebenarnya, seberapa pun tingginya harga bahan pangan, tidak akan menjadi masalah, atau dengan kata lain tidak akan menyebabkan krisis, selama semua lapisan masyarakat mampu membelinya. Namun dalam faktanya, senantiasa ada di tengah masyarakat orang-orang yang mampu dan yang tidak mampu. Masalahnya kemudian muncul ketika masyarakat yang tidak mampu tetap “dipaksa” untuk mendapatkan bahan makanan dengan cara membeli barang yang tidak terjangkau harganya. Sehingga dengan mekanisme ini, seseorang seolah tidak berhak makan jika dia tidak mampu menjangkau harga bahan pangan tersebut.
Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalis, di mana harga dijadikan sebagai pengendali tunggal distribusi barang di tengah masyarakat. Harga lah yang akan menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu, dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya sama sekali. Orang yang mampu membeli barang dengan harga tinggi, dia akan mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkannya. Sementara itu, orang yang tidak mampu sama sekali menjangkau harga barang tersebut, dia tidak berhak mendapatkanya, meskipun barang itu merupakan kebutuhan pokok baginya. Dalam kondisi yang kedua inilah krisis akan muncul. Dengan demikian, menjadikan harga sebagai usur pengendali tunggal distribusi, telah mengakibatkan buruknya distribusi barang di tengah masyarakat, yang berpotensi memunculkan terjadinya krisis sosial.
Jadi, krisis pangan saat ini secara fundamental tidak disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan yang dipengaruhi oleh
Semestinya, harga tidak dijadikan sebagai pengendali distribusi barang, apalagi barang kebutuhan pokok seperti bahan pangan. Sebab, barang kebutuhan pokok merupakan barang keperluan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat individu per individu. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok bagi seseorang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jika harga dijadikan sebagai pengendali distribusi, niscaya akan senantiasa ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk memenuhi bebutuhan pokoknya. Hal ini sangat berbahaya dan merupakan kedzaliman. Karena itu lah, dalam hal kebutuhan pokok, Islam mewajibkan negara untuk memberikan jaminan pemenuhan atas rakyatnya. Caranya, rakyat didorong untuk bekerja dan diberi kesematan untuk bekerja dengan membuka lapangan pekerjaan. Jika dengan cara ini masih dijumpai orang-orang yang tidak mampu, misalnya karena cacat atau lanjut usia, dan tidak ada anggota keluarga yang sanggup menopang kebutuhannya, maka negara wajib turun tangan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Sering muncul pertanyaan, dari mana pemerintah memperoleh dana untuk melakukan hal itu? Sebenarnya pemerintah
Islam telah memberikan contoh, bagaimana kesigapan negara dalam membantu rakyat yang kelaparan. Khalifah Umar bin Khaththab, di suatu malam, pernah melakukan inspeksi ke perkampungan penduduk. Tanpa sengaja beliau mendengar rintihan anak menangis dari arah sebuah rumah. Beliau pun menghampiri rumah tersebut dan memperhatikannya dari luar. Ternyata anak itu menangis karena lapar, sebab orang tuanya tidak lagi memiliki bahan makanan. Sang Ibu sudah mencoba menghibur anaknya, dengan seolah-olah sedang menanak makanan, padahal yang dimasak adalah batu. Si Ibu berharap anaknya tertidur sambil menunggu makanan yang sedang dimasak. Setelah mengetahui kondisi yang terjadi, sang Khalifah pun bergegas megambil sekarung bahan makanan dari Baitul Mal, lalu dipikulnya sendiri untuk diberikan pada keluarga yang sedang menghadapi kelaparan tersebut. Inilah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya.
Dalam konteks hubungan internasional, Islam juga menetapkan adanya kewajiban syar’i bagi Negara Khilafah untuk membatu negara lain yang membutuhkan bantuan pangan. Hal ini seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abdul Majid saat memimpin Kekhilafahan Turki Ustmani. Pada tahun 1845, terjadi kelaparan besar yang melanda Irlandia yang mengakibatkan lebih dari 1,000,000 orang meninggal. Untuk membantu mereka, Sultan Abdul Majid berencana mengirimkan uang sebesar 10,000 sterling kepada para petani Irlandia. Akan tetapi, Ratu
Tindakan seperti ini, praktis tidak pernah dilakukan oleh negara-negara kapitalis Barat terhadap negeri-negeri yang saat ini ditimpa krisis pangan seperti Eithopia, dll. Sebab, dalam prisip kapitalis “tidak ada makan siang gratis”, artinya tidak ada bantuan yang diberikan secara cuma-cuma, kecuali harus ada kompensasi tertentu. Maka, wajar jika kemudian terjadi kesenjangan yang lebar di dunia ini; di satu sisi ada negara-negara yang jumlah bahan pangannya melimpah dan di sisi lain ada negara yang rakyatnya kelaparan karena mengalami krisis pangan.
Jadi jelas, krisis pangan yang terjadi saat ini bukan karena jumlah pangan tidak mencukupi kebutuhan manusia, melainkan karena sistem distribusi yang buruk, akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. Seberapa pun produksi pangan bisa ditingkatkan, jika sistem distribusinya buruk, tetap saja akan terjadi krisis pangan. Dalam diskusi FKSK yang mengangkat tema “Awas Bahaya Krisis Pangan Global dan Nasional” baru-baru ini, terungkap betapa besarnya potensi pertanian di
hizbut-tahrir.or.id

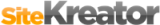
0 komentar:
Posting Komentar