Lebih dari 50 tahun, entah sadar atau tidak, negara-negara di Dunia Ketiga yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi ladang penjajahan negara-negara maju di bidang kesehatan. Atas nama kesepakatan internasional, negara-negara yang kondisinya lemah dan susah itu dipaksa tunduk dan taat terhadap kepentingan negara-negara maju yang dipimpin Amerika Serikat.
Salah satu bentuk penjajahan terselubung ini mulai terungkap ketika Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menggugat ketidakadilan organisasi kesehatan dunia (World Health Organisation/WHO) dalam kasus virus avian influensa (AI) atau dikenal sebagai flu burung melalui bukunya, Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Dunia kesehatan internasional terbelalak dengan keberanian ibu ini.
Selama lebih dari setengah abad 110 negara di dunia harus mengirimkan spesimen virus influensa kepada WHO dengan dalih adanya Global Influenza Surveillance Network (GISN) atau jaringan pengawasan influensa global. “Saya tidak mengerti siapa yang mendirikan lembaga yang sangat berkuasa tersebut,” kata Menkes.
Virus yang diterima GISN sebagai wild virus (virus liar) menjadi milik GISN. Virus ini kemudian diproses untuk risk assessment (penilaian risiko) dan riset para pakar serta pembuatan seed virus (bibit virus). Dari bibit virus inilah lalu dibuat vaksin dan kemudian dijual secara komersial ke seluruh dunia. Pembeli vaksin ini termasuk negara yang awalnya mengirimkan spesimen virusnya. Mereka tidak mendapatkan kompensasi apa-apa, misalnya harga vaksin yang lebih murah. Harga vaksin sepenuhnya ditentukan oleh produsen virus yang semuanya bercokol di negara-negara industri kaya. “Harganya sangat mahal tanpa mempedulikan alasan sosial kecuali alasan ekonomi semata. Sungguh nyata, suatu ciri khas kapitalistik,” kata Menkes dalam bukunya.
Modus serupa terjadi pada virus flu burung (H5N1). Ketika dunia heboh dengan virus mematikan ini, WHO pun memperlakukan aturan yang sama terhadap negara yang terjangkiti virus tersebut. Korban pertamanya adalah Vietnam. Di negara inilah virus flu burung ditemukan pada manusia. Dengan kekuasaannya WHO memaksa
Dalam kasus Vietnam itu, tiba-tiba di dunia beredar vaksin flu burung yang diperjualbelikan dengan harga yang tak terjangkau oleh negara-negara berkembang. “Ketika rakyat Vietnam meninggal gara-gara flu burung, di depan mata pedagang kulit putih menawarkan vaksin dengan Vietnam Strain. Alangkah tidak adilnya dunia ini!” kata Menkes.
Ia melanjutkan, “Sungguh sangat kejam bila penderitaan umat manusia diperdagangkan oleh manusia lain tanpa tatakrama!”
Apalagi, rantai produksi dan perdagangan tersebut melibatkan organisasi global dunia.
Awalnya virus H5N1 hanya menyerang Vietnam. Tahun berikutnya masuk Thailand dan Cina. Tahu-tahu virus ini pun menyusup ke Indonesia dengan korban pertama Iwan dan kedua putranya. Tak diketahui darimana virus itu berasal. Yang jelas, virus ini lebih ganas dibandingkan dengan virus yang ada di negara lain. Dalam kondisi ini, kata Menkes, Pemerintah pun melakukan sosialisasi penyakit mematikan ini dan menyediakan stok obat Tamiflu (nama generiknya Oseltamir yang diproduksi oleh Roche, salah satu perusahaan Amerika) dengan jumlah tertentu sesuai anjuran WHO.
Namun, apa yang terjadi? Setelah Pemerintah menyediakan dana, ternyata obat Tamiflu itu telah habis dipesan oleh negara-negara kaya sebagai stockpilling (persediaan). Padahal negara-negara tersebut tidak mempunyai satu pun kasus flu burung. “Ini kan tidak adil. Mereka tak punya kasus flu burung, tapi mborong obatnya,” kata Menkes.
Selain itu, WHO pun memerintahkan Indonesia untuk mengirimkan spesimen virusnya ke Hongkong untuk diagnosis. Proses diagnosis ini memakan waktu 5-7 hari. Ini tergolong lama karena pasien flu burung butuh penanganan cepat. Bahkan bila pasien memperoleh penanganan sebelum tiga hari, kemungkinan sembuh sangat besar. Ternyata hasil laboratorium di Hongkong ini sama dengan hasil pemeriksaan Litbangkes, Depkes. Ada apa dengan WHO?
Awal tahun 2007, Indonesia dikagetkan dengan munculnya vaksin virus flu burung Strain Indonesia yang dibuat perusahaan Australia, CSL. Padahal Indonesia tidak pernah mengirimkan spesimen virus tersebut ke negara lain, kecuali ke WHO. Usut punya usut, bibit virus itu berasal dari WHO Australia yang mendapatkan virus flu burung Indonesia dari WHO CC.
Kenyataan ini membuat Menkes menghentikan pengiriman spesimen virus ke WHO dan menggugat aturan yang ada. Tindakan tersebut ternyata membuat Amerika gerah. Malah satu pejabat AS mendatangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyatakan bahwa Menkes Indonesia tidak kooperatif. “Saya katakan, ‘Lho, apa urusannya saya dengan Amerika? Ini kan urusan saya dengan WHO,” kata Siti Fadilah.
Ia menyebut apa yang dilakukan oleh WHO sebagai kejahatan luar biasa dalam bidang kesehatan di dunia. Seharusnya organisasi tersebut melindungi umat manusia dari kesakitan, bukan malah membuat sakit. “Mekanisme yang ada justru lebih jahat dari bom atom,” kata Menkes.
Terbukti, WHO memang tidak bekerja untuk umat manusia. Organisasi ini bekerja untuk negara adidaya dan industri-industri obat multinasional. Bukti bagaimana organisasi kesehatan dunia ini bekerja untuk kepentingan Amerika bisa dilihat dari disimpannya seluruh data sequencing DNA virus flu burung WHO CC di Los Alamos, AS. Selama ini data-data virus itu hanya dikuasai oleh ilmuwan yang bekerja di Los Alamos. Ilmuwan lain di seluruh dunia tak bisa mengaksesnya, meski adalah data dunia.
Los Alamos National Laboratory yang berlokasi di New Mexico tersebut berada di bawah Kementerian Energi AS. Di tempat inilah dirancang bom atom yang menghancurkan Hiroshima tahun 1945. Disinyalir tempat ini menjadi tempat pembuatan senjata kimia dan biologi AS. Bukan tidak mungkin hasilnya nanti akan digunakan untuk menghancurkan negara yang dulunya pemilik virus, baik secara fisik dengan senjata itu sendiri, maupun secara ekonomi dengan memaksa suatu negara membeli produk-produk buatan mereka berupa obat-obatan.
Monopoli dan Proteksi
Joserizal Jurnalis, Ketua Presidium Mer-C, mengatakan bahwa selama ini dunia dipenuhi ketidakadilan. Negara maju mendominasi negara lemah dengan sangat nyata. “Kalau masalah virus saja dahsyatnya seperti ini, bagaimana dengan persoalan kesehatan lainnya?” katanya.
Ia memiliki data bagaimana negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim dipaksa membeli vaksin yang diproduksi negara-negara maju dan dilarang membeli produk dari negara-negara Muslim. Termasuk salah satu yang dilarang adalah vaksin produksi Indonesia yang dulu cukup laris di negara Dunia Ketiga.
Praktik monopoli kotor ini berlangsung lama tanpa dapat dicegah oleh Dunia Ketiga. Pasalnya, negara-negara maju selalu menggunakan lembaga internasional seperti WHO. Dalam soal vaksin, misalnya, 90 persen pasar vaksin dunia dikuasai hanya oleh sedikit perusahaan di negara maju. Perusahaan itu mendapat proteksi pemerintahnya untuk memproduksi dan mengedarkan produknya. Joserizal mengungkapkan, salah satu perusahaan vaksin terbesar saat ini ternyata milik Donald Rumsfeld (mantan menteri pertahanan AS).
Produksi dan peredaran obat di dunia kini dikuasai hanya oleh 15 perusahaan. Sembilan di antaranya adalah perusahaan AS seperti Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Upjohn, Wyeth, Eli Lilly, Schering-Plough, Abbott, dan GlaxoSmithKline. Lainnya adalah perusahaan dari Swedia, Jerman, Prancis, dan Swiss. Keuntungannya sangat luar biasa, melebihi keuntungan perusahaan di sektor lain.
Perusahaan-perusahaan itu mampu bertengger di papan atas dan menguasai pasar obat internasional karena berlindung di balik hak kekayaan atas intelektual atau hak paten. Biasanya perusahaan ini mendapatkan hak paten obat selama 20 tahun. Artinya, tidak boleh ada perusahaan lain yang memproduksi obat sejenis, kecuali membeli lisensinya.
Tidak aneh jika negara kaya memaksakan mekanisme TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ke negera-negara berkembang dalam masalah obat generik. Mekanisme ini mengharuskan perusahaan di negara berkembang membeli lisensi dari perusahaan papan atas negara maju dengan alasan supaya tidak terjadi kompetisi dalam lapangan obat-obatan generik. Tak cukup itu, perusahaan multinasional menuntut penambahan jangka waktu hak monopoli paten. Dengan sistem proteksi seperti ini tidak mungkin perusahaan-perusahaan obat di Dunia Ketiga memunculkan inovasi baru, kecuali hanya sebagai kepanjangan tangan perusahaan raksasa obat multinasional.
Di samping itu, WHO pun mengeluarkan standar layanan dan obat bagi suatu penyakit. Tentu standar ini menggunakan acuan internasional, yang notabene negara maju. Dengan mekanisme ini, pemerintah negara-negara berkembang mau tidak mau harus memenuhi standar itu. Dari satu sisi, standarisasi ini cukup baik. Namun, di sisi lain, standarisasi itu hanya bisa dipenuhi dengan membeli produk-produk perusahaan multinasional, baik peralatan medis maupun obat-obatannya.
Munculnya organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organisation) menjadi instrumen pengokoh dominasi negara maju atas negara berkembang dan miskin. Organisasi ini tidak hanya merampas kedaulatan ekonomi negara berkembang dalam sektor barang melalui GATT (General Agreement of Trade and Tariff), tetapi juga di sektor jasa melalui GATS (General Agreement on Trade Services). Dengan perjanjian ini, negara anggota WTO harus membuka pasarnya dalam hal barang dan jasa. Dalam kondisi seperti ini, pasti negara berkembang tak mampu bersaing.
Yang lebih aneh lagi, dalam kondisi tak berdaya, Pemerintah tidak mengambil langkah protektif dalam melindungi industri dan layanan kesehatan dalam negeri. Malah muncul niat untuk memprivatisasi sektor kesehatan. Rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya harus mampu berdiri sendiri tanpa bantuan Pemerintah. Pengelola layanan kesehatan tidak bisa lagi hanya berpikir bagaimana memberikan layanan kesehatan maksimal kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana mencari pemasukan bagi kelangsungan lembaganya.
Dampak
Mekanisme internasional dan kondisi dalam negeri yang runyam itu berdampak pada mahalnya layanan kesehatan dan harga obat-obatan di negara berkembang yang mayoritas penduduknya Muslim. Bagaimana tidak mahal jika semua obat harus dibeli dari luar negeri atau menggunakan lisensinya? Belum lagi, banyak peralatan kesehatan harus diimpor demi memenuhi standar internasional.
Wajar jika layanan kesehatan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Tidak salah jika kemudian muncul istilah, “Orang miskin dilarang sakit”, karena mereka tak akan pernah mampu membayar biaya kesehatan yang melangit. Apalagi banyak dokter yang sudah terjerat oleh perusahaan obat dan berpikir materialistis untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang sakit. Lengkaplah sudah penderitaan kaum papa.
Secara lebih luas, Dunia Ketiga semakin bergantung pada negara maju. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mandiri. Akhirnya, bangsa Dunia Ketiga hanya menjadi ajang jarahan bagi para penjajah untuk mengeruk keuntungan materi semata melalui peraturan internasional di bidang kesehatan. Benarlah yang dikatakan Siti Fadilah Supari, “Saatnya dunia berubah!” Tentu berubah ke arah sistem Islam. [Mujiyanto]

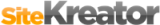
0 komentar:
Posting Komentar