Pengantar
Klaim bahwa Abu Hanifah an-Nu’man (80-150 H/700-768 M) liberal sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks metodologi dan hasil ijtihad beliau yang dikenal sebagai fuqaha’ (ahli fikih) ahl ar-ra’y, yang ketika itu memang menjadi fenomena fuqaha’ Kufah. Akan tetapi, apakah memang benar bahwa Imam Abu Hanifah liberal?
Untuk menjawab pertanyaan ini, sekaligus membuktikan benar dan tidaknya klaim tersebut, yang harus dianalisis pertama kali adalah fakta-fakta seputar dua mazhab besar yang berkembang pada waktu itu, yaitu mazhab Ahl al-Hadits dan Ahl ar-Ra’y, berikut metodologi dan hasil ijtihad mereka.
Pengklasifikasian para ulama ke dalam dua kategori tersebut sebenarnya lebih karena aktivitas mereka dalam mencari dasar-dasar yang menjadi landasan istinbâth (penggalian hukum) mereka. Sebagian mujtahid selalu mengaitkan pemahaman atas ‘ibârah (ungkapan secara literal) yang terdapat dalam nash, dan berhenti pada batasan makna yang ditunjukkan nash, lalu mengaitkan ijtihad mereka dengan makna-makna tersebut. Nah, mereka inilah yang kemudian dikenal dengan Ahl al-Hadits. Sebagian lain menganalisis makna-makna yang ditunjukkan oleh ‘ibârah nash yang bisa dijangkau oleh akal, sebagai tambahan terhadap makna-makna tekstualnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan mazhab Ahl ar-Ra’y.1
Fenomena ini sebenarnya bisa kita temukan ketika Nabi saw. masih hidup. Ketika beliau mengutus pasukan ke Bani Quraizhah, misalnya, beliau pernah bersabda: Alâ lâ yushallina ahad[un] al-’ashra illâ fî Bani Quraizhah (Ingat, jangan ada siapapun yang shalat Ashar, kecuali di Bani Quraizhah).2 Sebagian sahabat memahami perintah tersebut secara literal; mereka tidak shalat, kecuali seperti yang telah diperintahkan oleh Rasul, yakni setelah sampai di Bani Quraizhah. Mereka pun terpaksa mengakhirkan shalat Ashar, padahal untuk sampai di
Dari sini bisa dipahami, bahwa fenomena Ahl al-Hadits dan Ahl ar-Ra’y tidak bisa disederhakan; seolah-olah Ahl al-Hadits adalah mereka yang hanya menggunakan hadis, atsar, dan fatwa sahabat, sebaliknya meninggalkan jauh-jauh ra’y (akal/pandangan) mereka dalam berijtihad; sementara Ahl ar-Ra’y adalah mereka yang seolah-olah hanya berijtihad dengan menggunakan ra’y (akal/pandangan) mereka.
Latar Belakang Abu Hanifah
Abu Hanifah an-Nu’man (80-150 H/700-768 M) adalah salah seorang tâbî‘at-tâbi‘în. Beliau lahir ketika empat sahabat Rasulullah saw. masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi di Madinah, dan Abu ath-Thufail ‘Amir bin Wail di Makkah. Akan tetapi, beliau tidak sempat bertemu dengan mereka.
Beliau juga mempunyai banyak guru, antara lain: Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir Zain al-Abidin, Ja’far as-Shadiq, Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan, Jabir bin Yazid al-Ja’fi, Ibrahim an-Nakhai, dan as-Sya’bi. Di antara mereka, yang paling berpengaruh terhadap diri beliau adalah Hammad, fuqaha’ Kufah (w. 120 H). Beliau berguru kepada Hammad selama 22 tahun, hingga umur 40 tahun. Dari Hammad, beliau belajar fikih dan hadis. Beliaulah yang menggantikan Hammad untuk mengajar di Masjid Kufah, setelah beliau wafat. Satu hal yang patut dicatat, bahwa meski beliau berguru kepada Hammad, juga kepada Ibrahim an-Nakha’i, beliau mempunyai banyak pendapat yang berbeda dengan gurunya, sebagaimana yang ditulis oleh sahabat beliau, Muhammad bin al-Hasan, dalam kitabnya, al-Atsar. 6
Waki’ bin al-Jarrah, salah seorang fuqaha’ Kufah, pernah melukiskan majelis Abu Hanifah:
Bagaimana mungkin Abu Hanifah melakukan kesalahan, padahal bersama beliau ada Abu Yusuf dan Zafar yang terkenal dengan Qiyas-nya; Yahya bin Abi Zaidah, Hafsh bin Ghuyats, Hibban dan Mundil yang terkenal dengan hapalan hadisnya; al-Qasim bin Ma’an yang terkenal dengan pengetahuan bahasa Arabnya; Dawud at-Thai dan Fudhail bin Iyadh yang terkenal dengan kezuhudan dan kewaraannya? Selama yang mengikuti majelisnya seperti mereka, beliau tidak bisa melakukan kesalahan. Sebab, kalau beliau melakukannya, pasti mereka akan menyanggahnya. 7
Hanya saja, kecenderungan Abu Hanifah yang paling menonjol memang dalam penggunaan ra’y. Beliau bahkan dinobatkan sebagai Imam Ahl ar-Ra’y.8 Meski orang sering keliru, ketika beliau disebut-sebut sebagai Imam Ahl ar-Ra’y, seolah-olah beliau tidak menguasai hadis, atau bukan ahli hadis. Padahal, beliau juga mempunyai kitab hadis yang terkenal, Musnad Abi Hanifah, yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Mahmud al-Khuwarizmi (w. 655 H), dan diterbitkan di Mesir tahun 1336 H. Musnad ini setebal 800 halaman. Sahabat Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan, juga telah mengumpulkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dalam kitabnya, al-Atsar. Selain itu, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah juga melakukan hal yang sama, kemudian mengumpulkannya dalam kitab yang lain.9
Hanya saja, perlu digarisbawahi, bahwa konteks di mana Abu Hanifah dibesarkan memang ikut berpengaruh pada penerimaan beliau terhadap hadis. Seperti yang telah dimaklumi, bahwa di Irak—yang terkenal sebagai dâr adh-dharb (wilayah konflik)—telah terjadi banyak pemalsuan hadis. Karena itu, beliau sangat berhati-hati dalam menerima hadis, dan menetapkan syarat yang ketat, antara lain, hadis tersebut harus populer di kalangan orang-orang tsiqqah, dan perawinya juga tidak melakukan sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang diriwayatkan.10
Metodologi Abu Hanifah dan Implikasi Hukumnya
Memang, tidak bisa disangkal, selain kecenderungan Abu Hanifah yang kuat dalam menggunakan ra’y, latar belakang pendidikan, guru, dan kultur beliau yang dibesarkan di Irak juga ikut menentukan corak ijtihad beliau. Secara umum, Abu Hanifah sendiri telah menyangkal klaim-klaim orang yang menganggap seolah-olah bahwa beliau mengagungkan akalnya:
Saya heran dengan orang-orang yang mengatakan, seolah-olah saya telah berfatwa dengan ra’y. Padahal, saya tidak akan memberikan fatwa, kecuali dengan landasan atsar (riwayat, bisa as-Sunnah dan pendapat sahabat).
Bohong! Demi Allah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya lebih mendahulukan qiyas daripada nash; itu merupakan tuduhan bohong yang dituduhkan kepada kami. Apakah setelah dinyatakan nash, masih dibutuhkan qiyas?
Kami juga tidak akan menggunakan qiyas, kecuali ketika sangat terpaksa. Kalau kami tidak menemukan dalil, ketika itulah kami baru menggunakan qiyas atas apa yang didiamkan nash, berdasarkan manthûq (tekstual)-nya nash.
Kami, pertama-tama, akan mengambil Kitabullah, as-Sunnah, lalu keputusan sahabat, serta melakukan apa yang mereka sepakati. Kalau mereka berselisih, kami akan menganalogikan satu hukum pada hukum lain, dengan melihat persamaan ‘illat di antara kedua masalah tersebut, sampai maknanya benar-benar jelas.11
Kalau kemudian Abu Hanifah menggali suatu hukum dari hadis, yang notabene berbeda dengan ulama lain, jelas itu bukan karena kelancangan ataupun rekaan beliau, tetapi lebih karena kedalaman pemahaman beliau. Karena itu, Abu Yusuf, murid sekaligus mujtahid mazhab Hanafi, menyatakan, “Saya tidak menemukan ada orang yang lebih menguasai penjelasan hadis dan tempat-tempat fikih yang langka di dalam hadis melebihi Abu Hanifah.”12
Dari sini, bisa disimpulkan, bahwa secara metodologis, Abu Hanifah telah menetapkan sumber yang menjadi rujukan istinbâth beliau adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma, Qiyas dan Istihsân. Tentang penggunaan al-Quran tidak perlu dibahas, karena sudah jelas. Adapun tentang penggunaan as-Sunnah, beliau menggunakan hadis mutawâtir, masyhûr, dan ahad; serta menguatkan mana yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqqah. Sebagai contoh, Abu Hanifah tidak mengangkat tangan ketika rukuk dan i’tidal saat takbir intiqâl. Dalam kasus ini, al-Auza’i sempat berdebat lama dengan Abu Hanifah, karena al-Auza’i berpegang pada riwayat az-Zuhri, yang notabene mengangkat tangan, sementara Abu Hanifah berpegang pada riwayat Hammad, yang tidak mengangkat tangan. Ketika al-Auza’i mengatakan, “Saya memberitahukan kepada Anda hadis dari az-Zuhri dari Salim, dari ayahnya, lalu Anda menjawab, ‘Saya diberitahu Hammad dari Ibrahim.’” Abu Hanifah menjawab, “Hammad lebih fakih ketimbang az-Zuhri, dan Ibrahim lebih fakih ketimbang Salim, sementara Alqamah bukanlah ulama yang levelnya berada di bawah Ibn Umar. Kalau Ibn Umar adalah sahabat dan mempunyai kemuliaan sebagai sahabat, maka al-Aswad (sanad yang menjadi jalur Abu Hanifah) juga memiliki keutamaan yang besar.” Lalu al-Auza’i pun terdiam.13
Mengenai Ijma, Abu Hanifah menetapkan bahwa Ijma yang bisa digunakan adalah Ijma para mujtahid, yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah saw. dalam perkara syar’i, bukan ‘aqli, dan disetujui secara lisan, atau didiamkan seiring dengan perjalanan waktu.14 Adapun Qiyas—seperti yang beliau nyatakan sendiri—hanya digunakan karena sangat terpaksa. Dalam hal ini, mazhab Abu Hanifah membedakan Qiyas menjadi dua, yaitu Jalli (jelas) dan Khafi (tidak jelas).
Menurutnya, Qiyas Jalli adalah satu aspek yang langsung bisa dipahami, sementara aspek tersebut tidak bertentangan dengan aspek lain yang menuntut untuk di-tarjîh (dianalisis).15 Adapun Qiyas Khafi adalah Istihsân itu sendiri.16 Istihsân dijelaskan oleh al-Karkhi—salah seorang ahli ushul mazhab Hanafi—dengan: Mereposisi hukum dalam suatu masalah—sebagaimana hukum yang sama, yang ditetapkan pada yang lain—dengan hukum yang berbeda karena ada aspek yang lebih kuat, yang memang memaksa dilakukannya reposisi dari hukum yang pertama tersebut.17
Contoh, penjahit yang menghilangkan jahitannya karena dicuri orang, misalnya, tidak wajib mengganti pakaian yang hilang, karena tangannya adalah tangan amanah (yadun amânah), yaitu tangan yang hanya melakukan apa yang diminta oleh pengguna jasanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi saw. yang menyatakan: Lâ dhimâna ‘alâ mu’tamin (Tidak ada tanggungan bagi orang yang mendapatkan amanah). Akan tetapi, kesimpulan hukum ini harus direposisi dengan hukum kebalikannya (wajib mengganti), karena adanya aspek yang dianggap lebih kuat, yaitu alasan kalau penjahit tersebut tidak dikenai kewajiban mengganti, maka dia akan teledor. Karena itu, dengan logika istihsân, hukum mengganti pakaian yang hilang bagi penjahit tersebut menjadi wajib.
Inilah metodologi Abu Hanifah dalam konteks sumber yang menjadi rujukan istinbâth hukumnya. Adapun dalam konteks metodologi ijtihadnya sendiri, atau dalam konteks cara menganalisis nash syariat, maka beliau tidak hanya berpegang pada apa yang tersurat, tetapi juga berpegang pada ma’qûl an-nash. Misalnya, ketika fuqaha’ Ahl al-Hadits menyatakan bahwa zakat harus dikeluarkan seperti apa adanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam nash, maka Abu Hanifah menyatakan, bahwa zakat tidak harus dikeluarkan seperti apa adanya, tetapi boleh dibayarkan nilainya, sehingga bisa dibayar dengan uang atau makanan yang senilai dengan zakat tersebut. Di sinilah, letak kekhasan fuqaha’ Ahl ar-Ra’y.
Adapun dalam konteks metodologi istinbâth, atau dalam konteks makna bahasa yang bisa digunakan untuk memahami nash, Abu Hanifah—karena pertimbangan nalarnya—tidak hanya berpegang pada makna yang lazim digunakan orang. Misalnya, kebanyakan ulama menafsirkan hadis: Al-Bayyiâni bi al-khiyâr mâ lam yatafarraqâ (Penjual dan pembeli berhak untuk memilih—meneruskan jual-beli, atau membatalkannya—selama belum berpisah), dengan: berpisahnya majelis (tafarruq al-majlis). Sebaliknya, Abu Hanifah justu menafsirkannya dengan: berpisahnya ucapan (tafarruq al-qawl). Secara nalar, menurut Abu Hanifah, jual-beli tersebut sudah sempurna dengan adanya ijab dan qabul, sekalipun kedua belah pihak—penjual dan pembeli—belum berpisah dari majelis tersebut. Lalu, bagaimana mungkin, setelah terjadinya ijab dan qabul—yang notabene jual-belinya sudah sah—mereka masih bisa memilih, antara meneruskan atau membatalkan jual-belinya?
Justru dengan logika seperti ini, pandangan Abu Hanifah lebih sulit ketimbang ulama yang lain. Contoh lain yang berbeda, misalnya, dalam kasus tertawa dalam shalat. Abu Hanifah berpendapat, bahwa tertawa terbahak-bahak dalam shalat bukan saja membatalkan shalat, tetapi juga wudhu. Sebaliknya, ulama yang lain menyatakan, bahwa yang batal hanya shalatnya saja, sementara wudhunya tidak. Status hadis yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam kasus ini, ada yang yang mursal dan musnad, meski terbukti—sebagaimana hasil tarjîh (analisis) Wahbah az-Zuhaili—bahwa seluruh hadis yang statusnya musnad tersebut ternyata lemah, sehingga praktis Abu Hanifah justru menggunakan hadis mursal.18 Sebaliknya, ulama lain tidak menggunakan hadis tersebut, karena bisa jadi statusnya yang dianggap lemah. Dengan digunakannya hadis mursal seperti ini, justru pendapat Abu Hanifah lebih berat ketimbang pendapat jumhur.
Kesimpulan
Inilah gambaran bagaimana metodologi ijtihad Abu Hanifah dan implikasinya terhadap hukum yang dihasilkannya. Melalui paparan di atas, tidak bisa sedikitpun disimpulkan bahwa Abu Hanifah hanya menggunakan akalnya, dan meninggalkan nash, atau menggunakan akalnya secara leluasa, dan hanya sekali-kali merujuk pada nash. Tentu tidak demikian. Apa yang beliau lakukan tidak lain adalah ijtihad dengan menggunakan metodologi yang khas dan unik, sebagaimana metodologi yang juga digunakan oleh fuqaha’ Ahl al-Hadits.
Karena itu, klaim bahwa Abu Hanifah adalah liberal, atau menggali hukum dengan cara-cara liberal, tak lebih dari klaim-klaim pembenaran untuk menjustifikasi kerangka metodologis liberal, yang tidak mau terikat dengan Islam, dan nash-nashnya, apalagi pendapat para ulama salaf. Harapan mereka, dengan klaim-klaim pembenaran seperti itu, gagasan mereka akan mendapat tempat di hati kaum Muslim. Akan tetapi, jangan berharap, justru sebaliknya, umat akan semakin tahu kebohongan-kebohongan mereka yang mengatasnamakan para ulama salaf, seperti Abu Hanifah.
Wallâhu Rabb al-Musta‘ân wa ilayhi at-Tâkilan. [Hafidz Abdurrahman]
Catatan Kaki:
1 As-syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, Dar al-Ummah,
2 Al-Qurthubi, Tafsîr al-Qurthubi, XI/311.
3 Al-Qurthubi, ibid, XI/311.
4 Ibn Majah dalam Muqaddimah, Bab Fadh al-’Ulamâ’ wa al-Hatstsu ‘ala Thalab al-’Ilm, no. 234. Jamaluddin al-Muruzi berkomentar: Hadits ini diriwayatkan melalui jalur yang mencapai derajat hasan. Abu Hanifah, Musnad, Kitab al-’Ilm, hlm. 25.
5 Al-Khatib, Târîkh, III/32. Abu Hanifah, Musnad, Kitâb al-’Ilm, hlm. 25-26.
6 Dr. Ahmad as-Syarbasi, al-A’immah al-’Arba’ah, Dar al-Jil,
7 Ibid, hlm. 25.
8 Ibid, hlm. 11.
9 As-Syaikh ‘Ali as-Sayis, Târîkh al-Fiqh al-Islâmi, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Mesir, cet. I, 1999, hlm. 170-171.
10 Ibid, hlm. 172.
11 Dr. Ahmad as-Syarbasi, Op. Cit., hlm. 32.
12 Dr. Ahmad as-Syarbasi, Op. Cit., hlm. 33.
13 As-Syaikh ‘Ali as-Sayis, Op. Cit., hlm. 139.
14 Lihat, an-Nasafi, Kasyf al-Asrâr, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, t.t., III/137 dan 226-228; Amir Badsyah, Taysîr at-Tahrîr, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kaero, t.t., III/224; Ibn Amir al-Haj, at-Taqrîr wa at-Tahbîr, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, t.t., III/112; Ibn Najim, Fath al-Ghaffâr, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kaero, t.t., III/3.
15 Hafidh Tsana’allah az-Zahidi, Taysîr al-Ushûl, Dar Ibn Hazm, cet. II, 1997, hlm. 280.
16 Ibid, hlm. 280.
17 As-Sarakhsi, Ushul as-Sarakhsi, Dar al-Ma’rifah,
18 Lihat: Nashb ar-Rayah, I/47-54; Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, I/39.

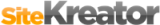
0 komentar:
Posting Komentar